
Lubdaka, Sang Pemburu Yang Mendapat Berkah di Siwa Ratri
Saya belum genap sebulan tinggal di Bali. Tugas negara menuntut saya menetap di sini dalam waktu yang tidak sebentar, memberi kesempatan untuk merasakan ritme kehidupan yang berbeda dari tempat asal saya.
Setiap hari menghadirkan pengalaman baru: jalan-jalan yang ramai dengan upacara adat, aroma dupa dan bunga yang menghiasi pura, hingga langit yang memunculkan panorama yang indah di pagi dan sore hari. Pun, saya juga mulai memperhatikan kalender masyarakat Bali, yang penuh dengan hari libur nasional dan fakultatif.
Hari suci Hindu pertama yang saya temui tahun ini adalah Siwa Ratri. Saya penasaran dan mulai mencari tahu, apa sebenarnya Siwa Ratri itu. Dari pencarian itu saya mulai paham, Siwa Ratri adalah malam Dewa Siwa. Malam yang dipercaya masyarakat Hindu sebagai malam pemberian berkat pengampunan.
Di malam Siwa Ratri, ada tiga hal yang harus dilakukan. Mona (tidak bicara), jagra (tidak tidur), upavasa (tidak makan dan minum). Siwa Ratri datang setahun sekali. Setiap Purwani Tilem ke-7 (bulan ke-7) tahun Caka. Tahun ini, jatuh pada hari Sabtu, 17 Januari 2026.
Saat googling lebih jauh, saya bertemu dengan kisah Lubdaka, cerita yang selalu dikaitkan dengan peringatan Siwa Ratri. Ternyata, saya pernah membaca kisah ini saat SD atau SMP dulu. Waktu itu, saya menganggapnya hanya cerita asing, tanpa kaitan apa pun dengan Indonesia. Tapi kali ini, berada di Bali dan mengalami Siwa Ratri, saya menyadari bahwa kisah Lubdaka hidup di tengah masyarakat, menjadi bagian dari pengalaman spiritual yang nyata bagi Masyarakat Hindu di Bali.
Lubdaka adalah seorang pemburu yang hidup dari hasil buruan, setiap hari.
Suatu hari, dia pergi ke hutan untuk berburu. Tetapi, suasana tidak seperti biasanya. Hingga malam hari, Lubdaka tidak mendapatkan satu buruan pun. Karena terjebak malam, Lubdaka terpaksa memanjat pohon agar selamat dari ancaman binatang buas. Ia bersandar di salah satu dahan. Untuk mengusir kantuk dan tetap terjaga dia memetik daun-daun hingga jatuh ke lingga di bawahnya.
Di pohon itu, Lubdaka mengalami epifani—sebuah titik balik spiritual yang membuka kesadarannya. Ia merasa berdosa karena selama ini membunuh binatang untuk bertahan hidup, dan dalam hening malam itu ia bertekad untuk tidak lagi berburu. Kesadaran itu muncul begitu saja, sederhana namun cukup kuat untuk mengubah arah hidupnya, meski ia tidak menyadari bahwa malam itu adalah Siwa Ratri. Dewa Siwa sedang bertapa, menyebarkan berkat bagi siapa pun yang merenung dan berserah, dan tanpa Lubdaka sadari, epifani itu diterima sebagai berkat.
Lubdaka pulang ke rumahnya dan menepati tekadnya. Ia meninggalkan panah dan senjatanya, memilih hidup sebagai petani. Tahun-tahun berikutnya, ia hidup sederhana, menjalani hari-hari dengan kesadaran baru, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Keberkahan malam Siwa Ratri tetap menyertainya, dan ia ditempatkan di Siwaloka sebagai pengakuan atas perubahan hati dan pemujaan yang tulus di malam itu.
Dari perspektif semiotika, Lubdaka menempati posisi yang unik. Ia adalah manusia biasa, penuh ketakutan dan keterbatasan, namun dari kesederhanaannya muncul makna yang kuat: ketidaktahuannya tentang malam Siwa tidak menghalangi berkat dan transformasi yang diterimanya. Titik buta, ketakutan, dan refleksi batin Lubdaka menjadi tanda bahwa epifani dan perubahan moral dapat muncul dari siapa saja, dan bahwa bahkan tindakan sederhana seorang individu biasa mampu memberi inspirasi dan makna bagi masyarakat luas.
Bagi saya, tinggal di Bali dan menyaksikan Siwa Ratri memberi pengalaman reflektif yang unik. Apalagi, malam sebelumnya saya sebagai muslim memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.
Dua malam gelap dan hening ini, yang bagi sebagian orang hanyalah hari libur, menjadi pengingat bagi saya bahwa transformasi sejati dimulai dari kesadaran diri sendiri. Dari merenungi keterbatasan, menerima ketakutan, dan membuka hati terhadap kehidupan di sekitar kita.
Bagi rekan-rekan Hindu yang menjalani Siwa Ratri. Selamat berkontemplasi.
Om Namah Shivaya!

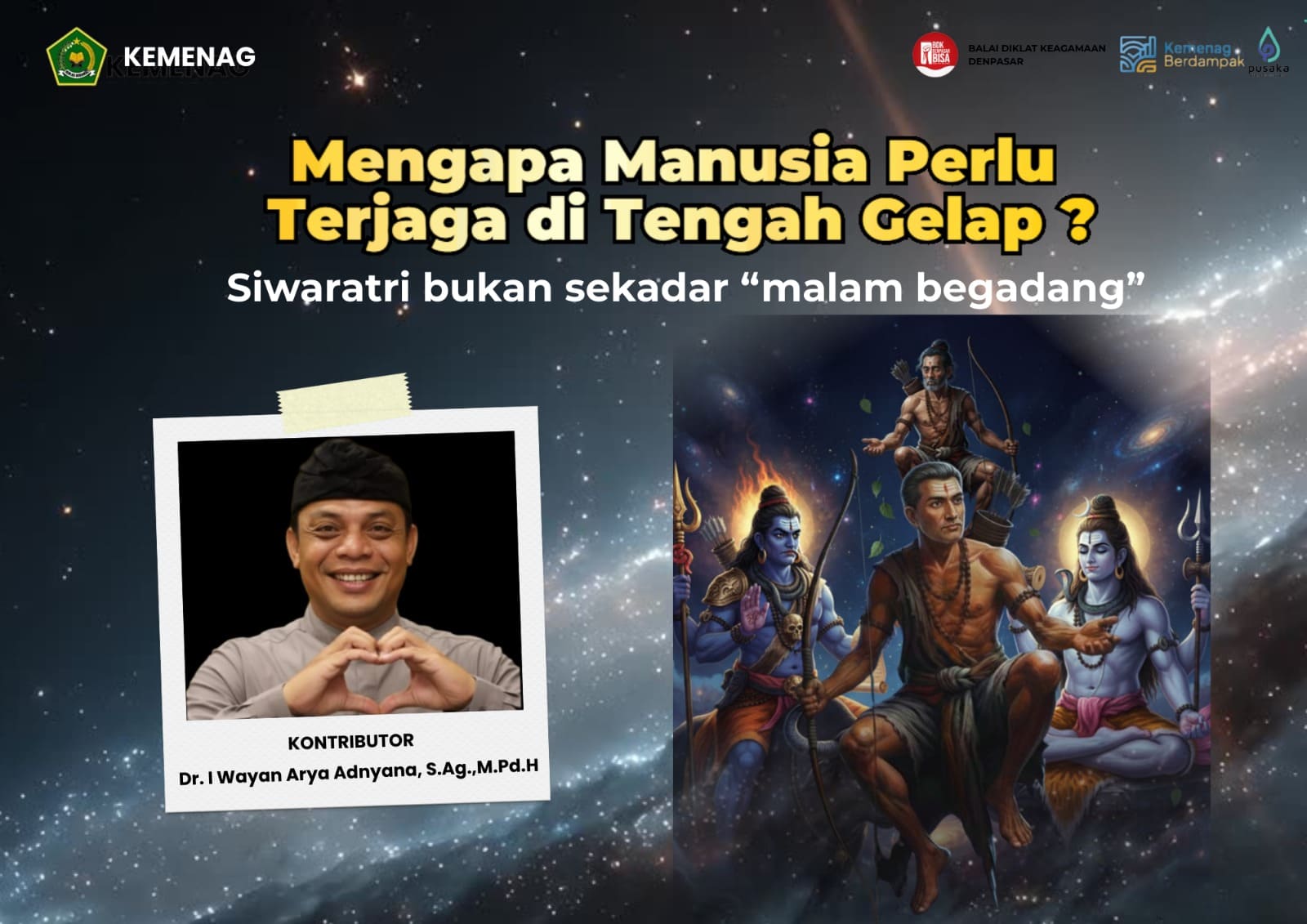

 5 Juni 2020
5 Juni 2020
 26 Desember 2022
26 Desember 2022