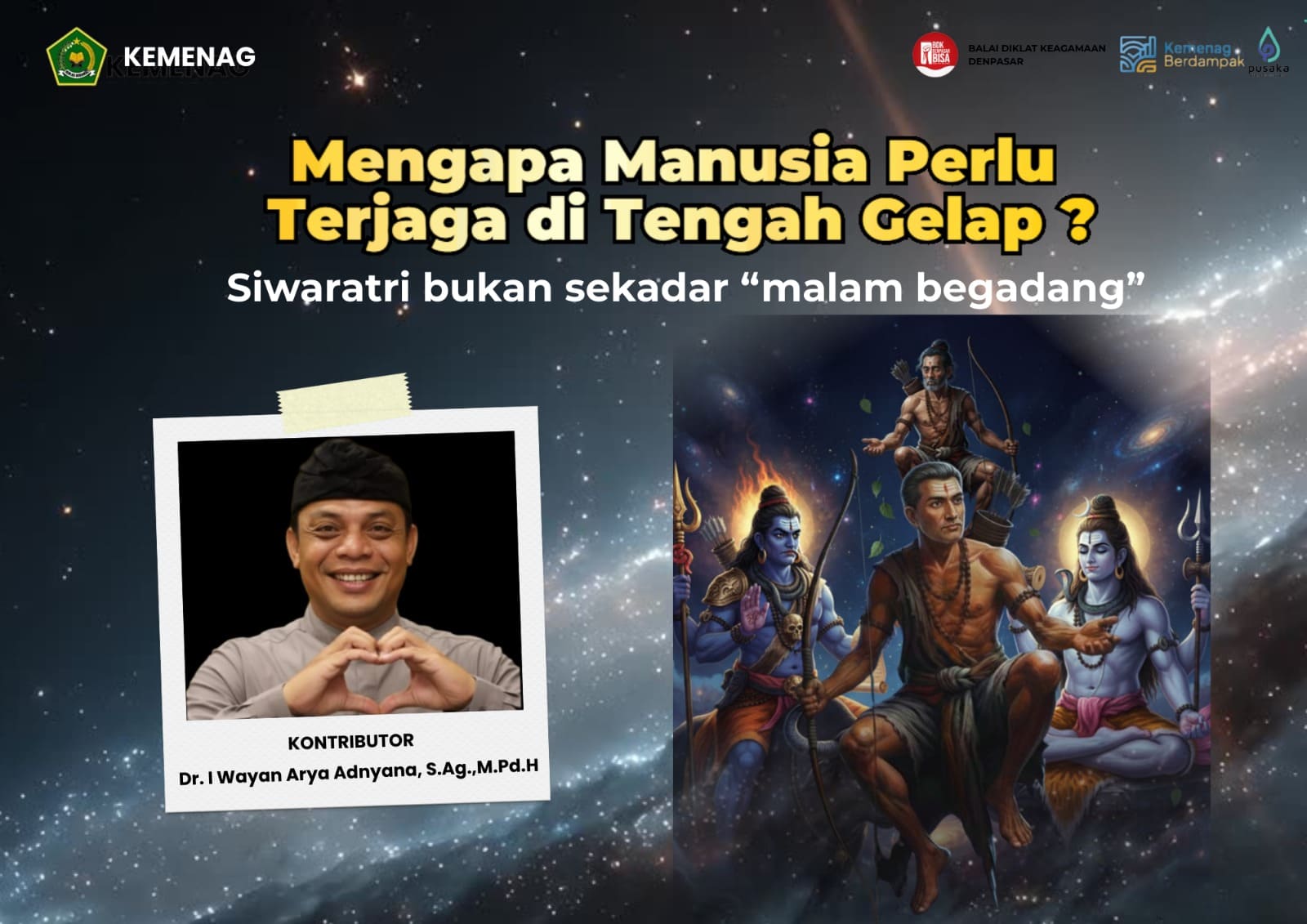
Mengapa Manusia Perlu Terjaga di Tengah Gelap
Siwaratri bukan sekadar “malam begadang”, melainkan malam simbolik—malam tergelap dalam setahun, yang jatuh pada Panglong 14, Purwaning Tilem, Sasih Kapitu—saat cahaya bulan hampir sepenuhnya lenyap dan kegelapan sedang menuju puncaknya. Ini adalah malam siwa, karena pemburu ini memujanya makanya diampuni dosanya. Dalam kosmologi Hindu, fase purwaning tilem bukan sekadar penanda waktu, melainkan momen peralihan yang kritis: saat terang mulai ditinggalkan, namun gelap belum sepenuhnya menguasai. Pada titik inilah kesadaran manusia diuji. Kegelapan bukan semata-mata sesuatu yang harus ditakuti, melainkan ruang sunyi tempat batin dipaksa jujur pada dirinya sendiri. Gelap tidak selalu identik dengan keburukan; sering kali justru di sanalah manusia berhadapan dengan dirinya tanpa topeng, tanpa distraksi, tanpa sandaran pada cahaya luar.
Karena itu, Siwaratri dimaknai sebagai malam introspeksi terdalam, ketika manusia tidak lagi bergantung pada terang eksternal, baik cahaya alam seperti bulan maupun cahaya buatan seperti lampu, layar, dan hiruk-pikuk peradaban, melainkan diajak menyalakan kesadaran dari dalam diri. Pada titik inilah relevansi Siwaratri menjadi nyata, perayaan ini mengarahkan manusia pada kesadaran batin, bukan sekadar pada pelaksanaan ritual lahiriah.
Manusia modern hidup di bawah cahaya yang nyaris tak pernah padam. Layar menyala sepanjang hari, informasi mengalir tanpa henti, dan kebisingan perlahan dianggap sebagai keniscayaan. Ironisnya, di tengah limpahan terang itu, manusia justru semakin sering kehilangan arah batinnya. Banyak yang terjaga secara fisik, tetapi tertidur secara eksistensial—hadir di mana-mana, namun absen dari dirinya sendiri. Siwaratri hadir sebagai kritik sunyi terhadap peradaban yang terlalu bising, sebuah ajakan halus untuk berhenti sejenak dan bertanya: masihkah manusia mampu terjaga secara batin, bukan sekadar sibuk secara lahiriah?
Makna ini menemukan bentuk naratifnya yang paling kuat dalam kisah Lubdaka, cerita inti Siwaratri yang tertuang dalam Kakawin Siwaratrikalpa karya Mpu Tanakung pada abad ke-15 Masehi, pada masa akhir Majapahit. Kisah ini lahir bukan dari zaman yang stabil, melainkan dari konteks krisis—ketika kekuasaan politik melemah, tatanan sosial goyah, dan manusia mencari pegangan makna yang lebih dalam. Sejak awal, Siwaratri memang berbicara dari ruang kegelisahan zaman, bukan dari kenyamanan sejarah.
Lubdaka digambarkan sebagai seorang pemburu, bukan figur ideal dan bukan pula simbol kesalehan ritual. Sosok ini merepresentasikan manusia yang hidup dari naluri, dari insting bertahan hidup, serta dari relasi yang keras dengan alam dan kehidupan. Gerak hidupnya berlangsung tanpa refleksi mendalam, dikuasai oleh kebutuhan sesaat. Namun justru figur semacam inilah yang ditempatkan sebagai pusat kisah Siwaratri, sebuah penegasan bahwa kesadaran bukan hak eksklusif orang-orang suci, melainkan kemungkinan yang terbuka bagi setiap manusia..
Pada suatu malam Panglong 14, tepat sehari sebelum Tilem, ketika kegelapan mulai mencapai intensitasnya dan hutan diliputi sunyi yang mencekam, Lubdaka tersesat dan terpaksa bermalam di atas pohon bilwa demi menghindari binatang buas. Malam itu terasa panjang, sunyi, dan penuh ketegangan. Rasa kantuk tak kunjung hadir. Dalam kewaspadaan dan ketakutan, Lubdaka terjaga sepanjang malam. Tanpa niat ritual, tanpa mantra, dan tanpa pengetahuan teologis, situasi tersebut justru menghadirkan pengalaman yang mewujudkan esensi terdalam Siwaratri.
Keadaan tersebut merepresentasikan makna jagra, terjaga dalam pengertian yang paling hakiki. Jagra tidak sekadar menunjuk pada kondisi tidak tidur secara fisik, melainkan pada kebangkitan kesadaran dari kelalaian hidup. Dalam filsafat Hindu, “tidur” kerap digunakan sebagai metafora bagi kehidupan yang dijalani secara mekanis, tanpa kehadiran reflektif. Pada malam itu, Lubdaka tidak lagi semata-mata hadir sebagai pemburu, tetapi tampil sebagai manusia yang mulai menyadari keberadaannya sendiri, ketakutan, penyesalan, dan keterbatasan yang bernama kematian.
Keheningan yang menyertai Lubdaka mencerminkan makna mona brata. Keadaan diam tersebut bukan lahir dari niat bertapa, melainkan dari situasi yang memaksa masuk ke ruang sunyi. Dalam tradisi spiritual, diam tidak dipahami sebagai ketiadaan suara, tetapi sebagai ruang tempat batin mulai berbicara. Mona menandai penghentian kebisingan ego, saat dorongan untuk bereaksi, membela diri, atau membenarkan diri mereda. Dalam keheningan inilah kesadaran Lubdaka beralih arah, penyesalan muncul bukan sebagai drama moral, melainkan sebagai kejujuran eksistensial yang tumbuh dari kedalaman batin.
Ketidakmampuan Lubdaka untuk makan sepanjang malam tidak lahir dari niat asketis yang dirancang secara sadar, melainkan dari situasi faktual: keterasingan di tengah hutan dan ketiadaan bekal. Tubuh berada dalam kondisi dipaksa melepaskan ketergantungan terhadap pemenuhan naluriah. Keadaan ini menghadirkan upawāsa bukan sebagai praktik ritual formal, melainkan sebagai pengalaman eksistensial. Dalam pengertian filosofis Hindu, upawāsa menunjuk pada proses pelepasan keterikatan terhadap dorongan indriawi sebagai jalan mendekatkan diri pada hakikat keberadaan.
Ketika dorongan instingtif melemah karena keterbatasan, ruang kesadaran justru terbuka. Lubdaka yang selama hidupnya digerakkan oleh naluri bertahan sebagai pemburu, pada malam itu berada dalam keadaan pengendalian diri yang muncul secara alami. Pengendalian ini tidak bersumber dari disiplin spiritual yang dipelajari, melainkan dari perjumpaan langsung dengan batas-batas eksistensi: rasa takut, keheningan, dan kesadaran akan kematian. Dalam situasi semacam itu, ego kehilangan dominasinya, dan batin dipaksa hadir sepenuhnya pada pengalaman yang sedang berlangsung.
Pada titik inilah jagra, mona, dan upawāsa bertemu dalam satu konfigurasi batin yang utuh. Ketiganya tidak berdiri sebagai laku terpisah, melainkan membentuk kondisi kesadaran yang, dalam tradisi filsafat yoga, dipahami sebagai keadaan keterpusatan batin. Yoga, dalam kerangka ini, tidak direduksi menjadi teknik tubuh atau rangkaian praktik fisik, melainkan dipahami sebagai kualitas kehadiran ketika perhatian tidak lagi tercerai oleh dorongan-dorongan instingtif dan batin berada dalam keadaan jernih serta terarah.
Lubdaka tidak sedang menjalankan yoga sebagai praktik yang disadari atau diniatkan. Justru kondisi batin itulah yang menghadirkan pengalaman yoga. Pada malam tergelap, tanpa simbol ritual, tanpa mantra, dan tanpa pengetahuan teologis, kesadaran muncul dalam bentuk yang paling mendasar yakni kehadiran manusia yang utuh di hadapan dirinya sendiri.
Dalam perspektif ini, Siwaratri tidak menawarkan kesalehan formal, melainkan kemungkinan transformasi batin yang lahir dari keberanian untuk terjaga, diam, dan mengendalikan diri di tengah keterbatasan hidup.
Daun-daun bilwa yang terlepas dari genggaman Lubdaka dan jatuh mengenai lingga Siwa tidak dapat dipahami sebagai tindakan ritual yang bersifat mekanis atau disengaja. Peristiwa tersebut justru memuat simbolisme yang subtil dan kaya makna. Dalam tradisi Siwaisme, bilwa dipahami sebagai pohon suci lambang kehidupan, keselarasan kosmis, dan relasi yang seimbang antara manusia dan alam. Lubdaka tidak menebang, tidak merusak, dan tidak mengeksploitasi pohon tersebut; keberadaannya di atas bilwa bersifat pasif dan lahir dari keterpaksaan situasional. Namun justru dari sikap non-destruktif inilah keselamatan muncul.
Simbol ini menyampaikan pesan ekologis yang mendalam: keselamatan manusia tidak lahir dari dominasi dan penaklukan terhadap alam, melainkan dari cara hidup yang selaras dengannya. Alam tidak ditempatkan sebagai objek yang boleh dieksploitasi demi kepentingan sesaat, tetapi sebagai ruang kesadaran yang menopang keberlangsungan hidup dan refleksi batin manusia. Dalam perspektif ini, relasi manusia–alam bukanlah relasi antara penguasa dan yang dikuasai, melainkan relasi etis yang menuntut tanggung jawab, penghormatan, serta kesadaran akan keterhubungan kosmis.
Ketika Lubdaka akhirnya meninggalkan kehidupan duniawi, kisah tidak berhenti pada romantisasi pengalaman spiritual semata. Narasi justru bergerak memasuki wilayah keadilan kosmis. Jiwa Lubdaka dihadapkan pada Yama, dewa kematian sekaligus hakim agung, simbol objektivitas hukum karma phala yang bekerja tanpa pandang bulu. Kehidupan Lubdaka sebagai pemburu tidak serta-merta dihapus oleh satu malam kontemplasi; setiap tindakan tetap memiliki konsekuensi etis. Penderitaan yang dialami mencerminkan prinsip dasar ajaran Hindu bahwa keadilan moral tidak pernah ditiadakan.
Namun pada titik inilah dimensi lain dari kosmologi Hindu ditampilkan. Kehadiran Dewa Siwa tidak dimaksudkan untuk meniadakan hukum karma, melainkan menghadirkan lapisan pemaknaan yang lebih dalam, yakni kesadaran. Jika Yama menimbang masa lalu berdasarkan perbuatan, Siwa merespons transformasi batin yang terjadi pada tingkat eksistensial. Pada malam Siwaratri, Lubdaka berada dalam keadaan yoga, terjaga, hening, dan mampu mengendalikan diri pada saat paling gelap dalam hidupnya. Perspektif Vedanta menekankan bahwa kesadaran memiliki daya transformatif yang tidak bekerja secara instan, tetapi perlahan dan mendalam, melampaui mekanisme sebab-akibat yang bersifat mekanis.
Dosa dan karma tidak dipahami sebagai sesuatu yang dapat ditebus secara langsung, melainkan sebagai realitas yang harus dijalani dan dimurnikan. Kesadaran tidak menghapus masa lalu, tetapi mengubah kualitas keberadaan. Seperti air keruh yang tidak serta-merta menjadi jernih ketika dituangi air bersih, tetapi perlahan berubah ketika air jernih terus mengalir, demikian pula kesadaran bekerja dalam diri manusia. Pengalaman Lubdaka pada malam Siwaratri menjadi aliran kesadaran yang seiring waktu, memurnikan arah hidupnya.
Perjumpaan antara Siwa dan Yama tidak dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai dialog kosmis antara keadilan dan kesadaran. Karma bekerja pada tataran tindakan lahiriah, sementara kesadaran bekerja pada tataran keberadaan. Lubdaka tidak memperoleh keselamatan karena masa lalunya suci, melainkan karena keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam kesadaran pada saat yang menentukan.
Relevansi Siwaratri saat ini menjadi semakin nyata. Jika Lubdaka tersesat di hutan belantara, manusia modern kerap tersesat di belantara digital, dalam pusaran ambisi tanpa arah dan rutinitas yang kehilangan makna. Senjata mungkin tidak lagi digenggam, tetapi ketidaksadaran tetap melukai diri sendiri, sesama manusia, dan alam.
Siwaratri mengajarkan pengekangan, bukan hanya terhadap hawa nafsu personal, tetapi juga terhadap keserakahan kolektif manusia terhadap alam. Terjaga berarti sadar akan dampak setiap tindakan. Diam berarti membuka ruang untuk mendengar suara alam yang selama ini terabaikan. Mengendalikan diri berarti mengambil secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Dalam kosmologi Siwaisme, Siwa dikenal sebagai Pashupati, pelindung seluruh makhluk hidup; kesadaran Siwa selalu berimplikasi pada tanggung jawab ekologis.
Krisis ekologis dewasa ini tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis atau manajerial, melainkan sebagai krisis kesadaran. Alam rusak bukan karena manusia kekurangan pengetahuan, melainkan karena kehilangan kehadiran batin dalam bertindak.
Siwaratri bukan perayaan kesempurnaan moral. Perayaan ini merupakan ajakan untuk berani sadar, bukan tentang penghapusan dosa secara instan, melainkan tentang kejujuran untuk menatap diri apa adanya dan kesediaan untuk dimurnikan secara berproses.
Pada malam Siwaratri manusia diajak mengajukan pertanyaan yang paling mendasar: apakah kehidupan dijalani dengan kesadaran, atau sekadar dengan keterjagaan fisik semata?
Selama manusia masih mungkin lupa pada dirinya sendiri, selama dunia tetap terlalu terang di luar dan gelap di dalam, Siwaratri tidak akan pernah kehilangan relevansinya.
Selamat Hari Raya Siwaratri



 5 Juni 2020
5 Juni 2020
 26 Desember 2022
26 Desember 2022