
Anjing adalah Kucing; Game Mind Changer di Meja Makan
Sore itu, pantai Jimbaran sebenarnya tidak dalam versi terbaiknya. Ombak bergemuruh. Angin bertiup sedang. Dan, suasana sepi. Langit pun tidak cerah, ada gelantung awan yang siap meledak menjadi hujan. Meski tidak dalam versi terbaik, Jimbaran tetaplah indah. Yang paling krusial, perut sedang dalam posisi puncak lapar akibat drama delayed pesawat yang semena-mena. Dan, kami harus segera mengisinya.
Sajian makanan belum muncul, tetapi ada pemandangan yang terasa mengganjal; anjing-anjing berkeliaran dengan jarak yang sangat dekat dengan meja makan.
Masalahnya sebenarnya bukan pada anjing itu. Masalahnya ada pada pengalaman yang sudah terkode rapi dalam sistem berfikir saya. Sepanjang hidup, saya tidak pernah makan dikelilingi anjing. Ruang makan saya selalu social in absentia dari anjing; yang hadir hanya kucing. Sesekali, cicak.
Ditambah lagi, dalam doktrin Islam di Indonesia, anjing adalah binatang yang menyimpan potensi najis pada liurnya. Tidak tanggung-tanggung, najis mugalladah.
Di titik ini, saya harus meminjam teori encoding Stuart Hall.
Dalam teori Hall, anjing bukan sekadar makhluk biologis, tetapi sign—tanda yang telah di-encoding oleh sistem makna tertentu: agama, budaya, pengalaman kolektif. Encoding anjing dalam pikiran saya berisi: najis, tidak suci, menakutkan, dan harus jaga jarak. Maka, ketika saya melihat anjing di sekitar tempat saya makan, kode itu bekerja aktif. Benturan pun terjadi antara tuntutan untuk memenuhi rasa lapar dan kehadiran anjing. Benturan sebenarnya tidak terjadi di ruang fisik, tetapi di ruang makna.
Untuk memberi ketenangan pikiran, saya melakukan rethinking atau de-coding. Saya mendekontruksi kode lama tentang anjing dan menggantinya dengan kode-kode baru. Saya tidak mengusir anjing, saya juga tidak meminta pemilik restoran menyingkirkan anjing-anjing, atasnama kenyamanan saya sebagai konsumen. Yang saya lakukan adalah melakukan kode ulang di pikiran saya, bahwa anjing-anjing ini adalah kucing.
Yang saya lakukan ini, oleh Stuart Hall, disebut sebagai negotiated decoding. Saya tidak sepenuhnya menerima makna dominan yang lama, tetapi juga tidak menolaknya secara frontal. Saya menegosiasikannya. Tanda yang sama—anjing—dibaca dengan kode lain. Tubuhnya tetap anjing, tetapi maknanya bergeser.
Hasilnya bukan sekadar “tenang”. Hasilnya adalah kembalinya selera makan. Makan pun jadi nikmat, bukan karena anjing menghilang, tetapi karena makna tentang anjing tidak lagi menguasai ruang batin dan pikiran.
Dalam perspektif ini, mind changer bukan ilusi. Ia adalah praktik decoding. Dunia tidak berubah, tetapi relasi kita dengan dunia berubah. Dan relasi itulah yang menentukan makna selanjutnya.
Stuart Hall mengingatkan: makna tidak pernah final. Ia selalu diproduksi, direproduksi, dan bisa dinegosiasikan. Di Jimbaran sore itu, saya belajar satu hal sederhana namun radikal: kadang yang perlu kita ubah bukan objeknya, melainkan kode yang kita gunakan untuk membacanya.
Anjing tetap anjing. Tetapi bagi pikiran, ia bisa menjadi kucing.
Dan di situlah, saya menemukan kebebasan untuk menikmati sajian ini, senikmat-nikmatnya.


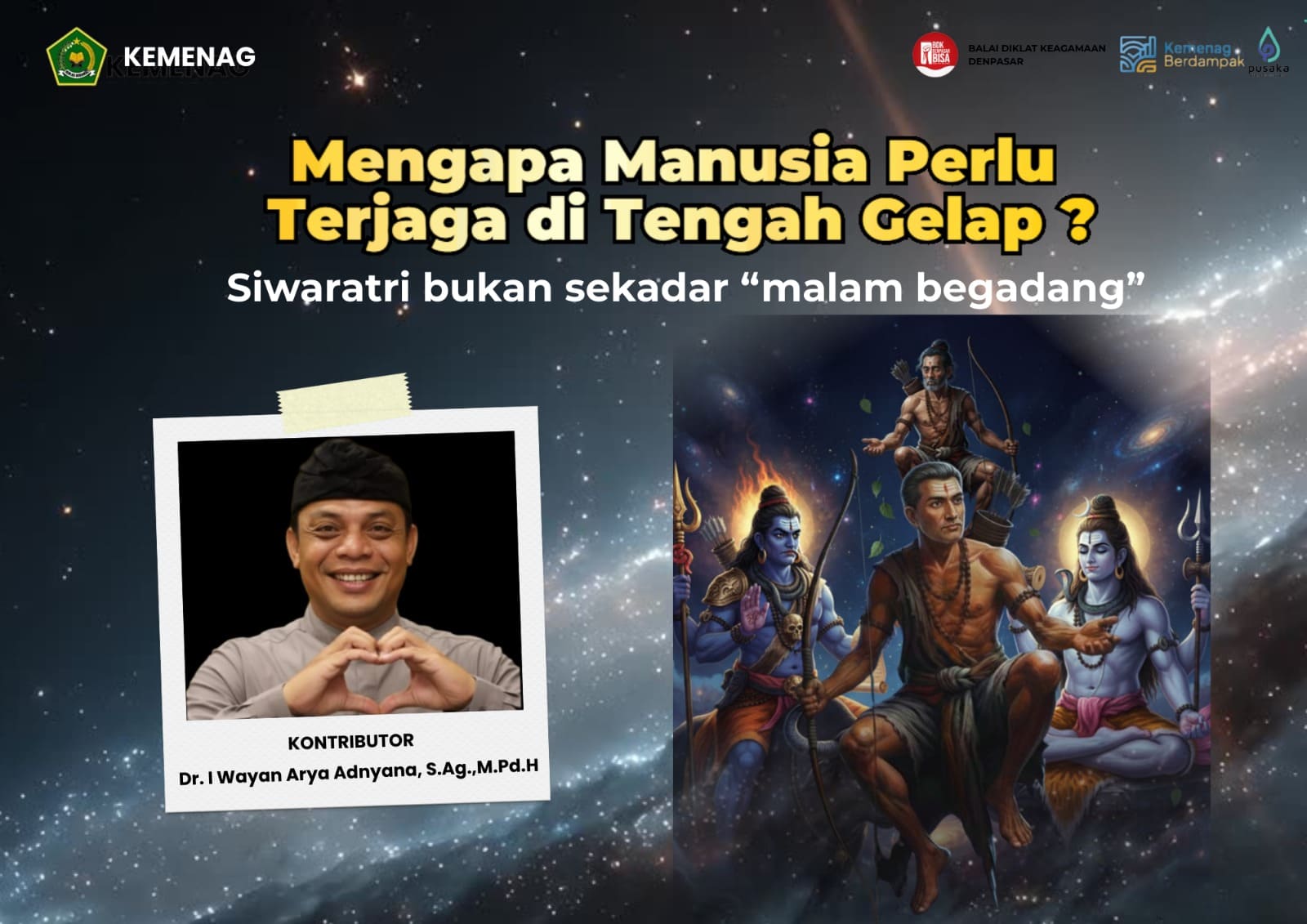
 5 Juni 2020
5 Juni 2020
 26 Desember 2022
26 Desember 2022