
Menelusuri Kedalaman Ontologis Pegat Wakan dalam Transformasi Spiritual Umat
Kehidupan spiritual masyarakat Hindu di Nusantara, khususnya yang berakar pada tradisi Bali, merupakan sebuah simfoni panjang yang memadukan gerak mikrokosmos dan makrokosmos dalam satu tarikan napas pengabdian. Di jantung orkestra ritual ini, terdapat sebuah siklus yang dikenal sebagai Galungan dan Kuningan, sebuah periode 42 hari yang melampaui sekadar perayaan kemenangan mitologis. Siklus ini adalah sebuah laboratorium batin, sebuah ruang waktu di mana manusia ditempa untuk mengenali hakikat dharma di tengah hiruk-pikuk adharma. Puncak penutup dari perjalanan panjang ini adalah Pegat Wakan, sebuah titik henti yang sering kali terabaikan dalam keriuhan seremonial, namun sesungguhnya menyimpan kunci utama bagi keberlanjutan spiritualitas umat. Pegat Wakan bukan sekadar akhir dari sebuah kalender liturgi, melainkan sebuah transformasi kesadaran dari bentuk lahiriah menuju esensi batiniah yang sunyi namun bertenaga.
Pegat Wakan dalam Jalinan Kalender Suci
Memahami Pegat Wakan memerlukan ketelitian dalam melihat struktur waktu yang melingkupinya. Dalam kosmologi Hindu Bali, waktu bukanlah garis lurus yang dingin, melainkan lingkaran suci yang bernapas. Pegat Wakan jatuh pada hari Rabu Kliwon, wuku Pahang. Penetapan waktu ini sangat krusial karena ia menandai genapnya 42 hari sejak dimulainya persiapan spiritual pada hari Sugimanek Jawa. Periode enam minggu ini merupakan durasi yang dianggap cukup bagi seorang manusia untuk melakukan regenerasi seluler maupun spiritual, sebuah masa inkubasi di mana nilai-nilai kebajikan ditanam, dipupuk, dan akhirnya dipanen.
Secara etimologis, istilah Pegat Wakan atau Pegat Uwakan menawarkan kedalaman makna yang berlapis. Kata pegat dalam bahasa Jawa Kuna dan Bali memiliki arti putus, berakhir, atau terlepas. Sementara itu, wakan atau warah merujuk pada bicara, kata-kata, instruksi, atau pengajaran. Ada pula yang menghubungkannya dengan uwakan yang berarti kembali. Jika makna-makna ini disatukan, Pegat Wakan adalah sebuah kondisi di mana "pembicaraan" atau instruksi spiritual dari kekuatan ilahi dan leluhur telah berakhir. Selama periode Galungan dan Kuningan, umat diyakini sedang berada dalam fase briefing spiritual, sebuah masa di mana para Dewa dan Pitara turun ke bumi untuk memberikan bimbingan dan energi. Ketika Pegat Wakan tiba, instruksi tersebut dianggap selesai karena manusia kini telah dibekali dengan jnyana atau pengetahuan suci yang cukup untuk melangkah mandiri.
Transisi ini sangat penting dalam pembinaan umat. Umat diajarkan bahwa spiritualitas tidak boleh bergantung selamanya pada stimulus eksternal atau ritual formal. Ada saatnya suara-suara instruksi harus berhenti agar suara hati nurani dapat terdengar lebih jelas. Pegat Wakan adalah momen di mana manusia "memutus" ketergantungannya pada keramaian ritual untuk kemudian membawa substansi ritual tersebut ke dalam kesunyian hidup sehari-hari.
Inti dari Galungan adalah kemenangan dharma atas adharma. Namun, dalam konteks Pegat Wakan, kemenangan ini harus dimaknai ulang sebagai sebuah pencapaian kualitas batin yang stabil, bukan sekadar kemenangan sesaat dalam sebuah perayaan. Dharma, dalam pengertian yang lebih dalam, adalah hukum kebenaran abadi yang menopang alam semesta, sementara adharma adalah segala sesuatu yang menyebabkan kekacauan pikiran (byaparaning idep).Segala bentuk kegelisahan, kebencian, ketamakan, dan kebingungan adalah wujud nyata dari adharma yang bersemayam di dalam citta atau alam pikiran manusia.
Pegat Wakan mengingatkan umat bahwa pertarungan antara dharma dan adharma adalah sebuah proses yang bersifat kontinu. Galungan pertama kali dirayakan di Bali pada tahun 882 Masehi bukan hanya untuk mengenang jasa para dewa, tetapi untuk menetapkan sebuah tonggak pengingat bagi manusia agar selalu menajamkan daya spiritualnya. Tanpa adanya penajaman spiritual, manusia akan mudah terperosok ke dalam asura sampad atau kecenderungan keraksasaan, yang dicirikan oleh dominasi indra dan pengejaran kenikmatan duniawi semata.
Pegat Wakan berfungsi sebagai fase evaluasi. Apakah selama 42 hari ini kita benar-benar telah berhasil menaklukkan Sad Ripu? Bagian-bagian dari Sad Ripu—kama (hawa nafsu), lobha (rakus), kroda (marah), mada (mabuk), matsarya (iri hati), dan moha (bingung)—adalah musuh internal yang sering kali lebih berbahaya daripada musuh eksternal. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu membedakan dorongan hidup yang berasal dari budhi atma (suara kebenaran) dengan dorongan yang hanya memuaskan ego. Pegat Wakan adalah saat di mana "perang" besar itu beralih menjadi "perdamaian" batin yang kokoh.
Keseimbangan hidup yang diusung dalam konsep Tri Hita Karana—hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam—menjadi tolok ukur utama keberhasilan kemenangan dharma tersebut. Implementasi nyata dari kemenangan ini dalam kehidupan modern bukan lagi soal mengangkat senjata, melainkan kejujuran di tengah godaan korupsi, ketulusan di tengah iklim kompetisi yang tidak sehat, dan keberanian untuk membela keadilan meskipun sulit.
Metafora Penjor dari Eksistensi Menuju Esensi
Ikonografi paling megah dari rangkaian Galungan adalah penjor. Namun, pada hari Pegat Wakan, kemegahan ini harus ditiadakan melalui ritual pencabutan penjor. Pencabutan ini menyimpan makna kontemplatif yang sangat dalam tentang hakikat pelepasan atau vairagya. Penjor yang menjulang tinggi dengan segala hiasannya adalah simbol dari Gunung Agung, stana para dewa, sekaligus wujud syukur atas kemakmuran yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Secara anatomis, penjor merupakan representasi naga yang sakral. Bambu yang melengkung adalah tubuh naga, hiasan janur (busung) adalah rambut naga, dan hasil-hasil bumi yang digantungkan padanya adalah simbol dari Sandang dan Pangan yang tumbuh dari bulu-bulu Naga Anantabhoga. Memasang penjor pada hari Penampahan adalah tindakan menyatakan eksistensi bakti umat di hadapan Tuhan. Namun, mencabutnya pada hari Pegat Wakan adalah tindakan kembali menuju esensi.
Pencabutan penjor mengajarkan umat tentang ketidakkekalan materi. Segala keindahan janur yang tadinya segar dan berwarna-warni, pada hari Pegat Wakan telah mengering. Ini adalah pengingat visual bahwa tubuh fisik dan segala pencapaian duniawi suatu saat akan mengalami pelapukan yang sama. Yang tersisa bukanlah bambunya, melainkan nilai-nilai spiritual yang telah diserap selama penjor itu berdiri tegak di depan pintu rumah. Kekuatan hidup atau pikukuh jiwa urip kini tidak lagi berada pada bambu yang melengkung, tetapi pada integritas pribadi yang telah ditempa selama masa Galungan.
Melalui ritual ini, umat dibina untuk tidak terjebak dalam berhala materi. Banyak umat yang merasa sayang untuk mencabut penjor karena harganya yang mahal atau bentuknya yang indah. Namun, secara spiritual, mempertahankan penjor setelah Pegat Wakan adalah sebuah bentuk kegagalan dalam memahami siklus pelepasan. Ketidakmampuan untuk melepaskan bentuk lahiriah menunjukkan bahwa batin masih terikat pada ego dan pamer kemewahan (rajasika), padahal yang diharapkan adalah pencapaian kondisi sattwika yang hening dan bersahaja.
Abu dan Bungkak Nyuh
Puncak dari ritual Pegat Wakan yang paling esoteris adalah proses pembersihan atribut penjor yang kemudian dibakar. Abu dari pembakaran hiasan penjor ini tidak dibuang begitu saja, melainkan dimasukkan ke dalam bungkak nyuh (kelapa muda, biasanya jenis kelapa gading) dan ditanam di belakang pelinggih rong tiga (Kemulan) atau di lingkungan halaman rumah.
Ritual ini adalah sebuah tindakan alkimia spiritual. Api (teja) digunakan untuk mentransformasi materi menjadi abu. Abu mewakili residu dari pengalaman suci yang telah dilalui. Memasukkannya ke dalam kelapa muda—yang airnya disimbolkan sebagai air suci kehidupan (amrita)—dan menanamnya ke dalam bumi (pretiwi) adalah simbolisme pengembalian unsur-unsur mikro kepada makrokosmos. Tindakan menanam ini disertai dengan canang sari sebagai wujud doa memohon kesuburan dan keberkahan bagi alam semesta.
Secara kontemplatif, proses ini menggambarkan bagaimana seorang umat seharusnya "menanam" benih-benih kebaikan yang didapat dari perayaan hari raya ke dalam lubuk hati terdalam. Penanaman ini bermakna bahwa dharma tidak boleh hanya berhenti sebagai wacana atau euforia, tetapi harus berakar kuat dalam diri agar dapat tumbuh menjadi perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Abu yang ditanam adalah simbol dari "ego yang telah terbakar" oleh api jnyana, yang kini siap untuk memupuk kehidupan baru yang lebih suci.
Ini adalah bentuk nyata dari ajaran mamasuh malaning bumi—sikap proaktif dalam menjaga harmoni dan keselarasan bumi yang telah terinteraksi dengan elemen-elemen ketuhanan. Umat diajarkan bahwa kesucian tidak hanya didapat di pura, tetapi juga melalui cara kita memperlakukan sisa-sisa ritual dengan penuh hormat. Kesadaran ekoteologis ini sangat relevan untuk ditanamkan kepada umat di tengah krisis lingkungan global, di mana ritual agama harus menjadi pelopor dalam pelestarian alam.
Eksplorasi yang lebih dalam terhadap Pegat Wakan membawa kita pada teks filsafat Wrhaspati Tattwa, yang mengupas tentang pengendalian batin untuk mencapai kehidupan yang rukun dan harmonis. Dalam teks ini, kondisi spiritual yang paling tinggi dicirikan oleh kemampuan seseorang untuk menguasai citta (alam pikiran). Pikiran adalah penyebab utama apakah seseorang akan mengalami keselamatan atau kebinasaan, kesedihan atau kebahagiaan.
Pegat Wakan, dalam kacamata Wrhaspati Tattwa, adalah sebuah metafora untuk kondisi Paramartha. Paramartha diibaratkan seperti akasa (ruang hampa atau angkasa) yang bersifat nisabda—tidak bersuara atau hening mutlak. Deskripsi puitis tentang kondisi ini adalah awang-awang malilang, sebuah ruang kosong yang sangat jernih, terang, dan tanpa noda. Bagi umat, Pegat Wakan adalah ajakan untuk memasuki ruang keheningan ini setelah 42 hari dipenuhi dengan suara genta, mantra, dan hiruk-pikuk sosial.
Pegat Wakan adalah sebuah latihan bagi umat untuk merasakan "kematian ego" sebelum kematian fisik yang sesungguhnya tiba. Kemampuan untuk tetap tenang (nirlopamantarapamam) di tengah dinamika dunia adalah buah dari dharma yang sejati. Umat dibina untuk menjadi pribadi yang nirdvandva, yaitu mereka yang tidak lagi terombang-ambing oleh dualitas: tidak berlebihan dalam kegembiraan saat menang, dan tidak hancur dalam kesedihan saat gagal.
Manifestasi Pegat Wakan dalam Realitas Sosial
Refleksi keagamaan tentang Pegat Wakan harus mampu menyentuh aspek praktis kehidupan umat. Bagaimana nilai keheningan dan pelepasan ini diterjemahkan dalam interaksi sosial? Konsep Tepa Salira (tenggang rasa) dan Mangasah Mingising Budi (mempertajam keluhuran budi) menjadi relevan di sini. Pegat Wakan adalah saat di mana umat melakukan "penyucian kata-kata" (Pegat Wakan = memutus bicara yang sia-sia).
Dalam tradisi Jawa dan Bali, terdapat kebijaksanaan yang mengatakan bahwa dalam
mengucapkan kata-kata jangan sampai menyinggung perasaan orang lain (Wijil = keluar). Pegat Wakan menuntut umat untuk lebih banyak mendengarkan suara batin daripada memproduksi suara-suara luar yang sering kali penuh dengan gosip, caci maki, atau kebohongan. Di era digital, ini berarti memiliki pengendalian diri dalam menggunakan media sosial—memutus rantai penyebaran kebencian dan hoaks sebagai bentuk nyata dari pengamalan dharma.
Selain itu, nilai kebersamaan yang dirasakan selama Galungan melalui tradisi Ngejot (berbagi makanan) harus ditransformasikan menjadi solidaritas sosial yang berkelanjutan. Pegat Wakan bukan berarti kita berhenti peduli pada sesama setelah ritual usai. Sebaliknya, kasih sayang yang didapat dari leluhur dan dewa harus "dialirkan" kembali kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kita.
Umat juga diajak untuk mencontoh karakter Dharma dalam kisah Mahābhārata—sosok yang rajin, pandai mengatur waktu antara belajar, bekerja, dan berdoa, serta memiliki disiplin yang tinggi. Disiplin waktu yang diajarkan dalam perayaan Kuningan (di mana persembahyangan dibatasi hingga tengah hari) harus berlanjut menjadi profesionalisme dalam pekerjaan sehari-hari setelah Pegat Wakan.
Menyingkap Cahaya di Balik Kegelapan, Peran Jnyana dan Kesadaran Atma
Puncak dari seluruh renungan Pegat Wakan adalah penemuan jati diri yang sejati atau Atmajnana. Dalam Katha Upanishad, dijelaskan bahwa untuk meraih pengetahuan tentang Diri Ilahi yang sangat halus, seseorang harus memiliki semangat pelepasan dunia yang mendalam serta keazaman murni. Manusia sering kali tergoda oleh "lembu-lembu tua" atau hal-hal duniawi yang tidak berguna, padahal yang dicari adalah kekayaan spiritual yang abadi.
Pegat Wakan adalah momen di mana umat diingatkan kembali bahwa tubuh jasmani ini hanyalah sebuah kendaraan, sedangkan pengendara sejatinya adalah Atma yang berasal dari Tuhan. Setelah semua perhiasan penjor yang indah dilepaskan dan dibakar menjadi abu, kita menyadari bahwa kemegahan yang sesungguhnya ada di dalam, bukan di luar. Kesadaran ini membawa pada rasa puas diri sendiri (atmanastusti), sebuah kondisi di mana kebahagiaan tidak lagi bergantung pada kepemilikan materi.
Cahaya suci atau Adanu harus terus bersinar di dalam hati, bahkan setelah lampu-lampu hari raya dipadamkan. Pengetahuan suci (Jnyana) yang telah dipelajari selama masa Galungan harus menjadi obor yang menerangi kegelapan dunia (timira). Dalam teks-teks Hindu, Tuhan digambarkan sebagai Yang Esa namun disebut dengan banyak nama oleh para bijaksana. Pegat Wakan menyatukan keberagaman nama dan bentuk ritual itu kembali ke dalam Ketunggalan yang sunyi di dalam diri.
Bagi generasi muda Hindu, keterlibatan dalam pelestarian budaya seperti tradisi Ngelawang (menari barong untuk mengusir aura negatif) bukan sekadar atraksi seni, melainkan proses mendidik diri tentang nilai-nilai luhur dan identitas budaya yang kuat. Pegat Wakan menjadi titik awal bagi mereka untuk membawa identitas budaya tersebut ke dalam kancah persaingan global dengan integritas moral yang tidak tergoyahkan.
Pegat Wakan sebagai Gerbang Menuju Kehidupan Baru
Pegat Wakan bukanlah akhir dari sebuah rangkaian tanpa makna, melainkan sebuah gerbang transformasi. Ia adalah titik di mana "instruksi" berubah menjadi "aksi," di mana "kemegahan" berubah menjadi "keheningan," dan di mana "perayaan" berubah menjadi "kesadaran." Melalui prosesi pencabutan penjor dan penanaman abu dalam bungkak nyuh, umat diajarkan tentang siklus kehidupan yang agung: penciptaan (srsti), pemeliharaan (sthiti), dan peleburan (pralina).
Dalam pembinaan umat, renungan tentang Pegat Wakan harus ditekankan sebagai momen untuk memerdekakan batin. Kemerdekaan batin tercapai ketika kita mampu memutus keterikatan pada ego yang selalu merasa benar, nafsu yang tidak pernah puas, dan kebencian yang merusak harmoni. Pegat Wakan mengajak kita untuk "pulang" ke dalam rumah diri yang sejati, di mana Tuhan bersemayam dalam keheningan yang bersih.
Setelah 42 hari berjuang di medan Kuruksetra batin, Pegat Wakan memberikan kita "istirahat" spiritual yang berkualitas. Namun, istirahat ini bukanlah kelalaian (apramada), melainkan pengumpulan tenaga baru untuk menjalani hari-hari mendatang dengan semangat dharma yang lebih segar. Kemenangan dharma yang dirayakan saat Galungan kini telah "menitis" ke dalam setiap denyut nadi dan setiap helai napas umat.
Mari kita jadikan momentum Pegat Wakan ini sebagai spark atau percikan semangat untuk selalu menegakkan kebaikan di dalam diri sendiri terlebih dahulu, sebelum kita mencoba membenahi dunia luar. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa menganugerahkan tuntunan, kedamaian, dan keseimbangan bagi kita semua, agar cahaya kesucian yang telah kita nyalakan selama Galungan dan Kuningan tidak pernah padam, melainkan terus berpendar menerangi jalan menuju pencerahan sejati.
Om Shanti Shanti Shanti Om.


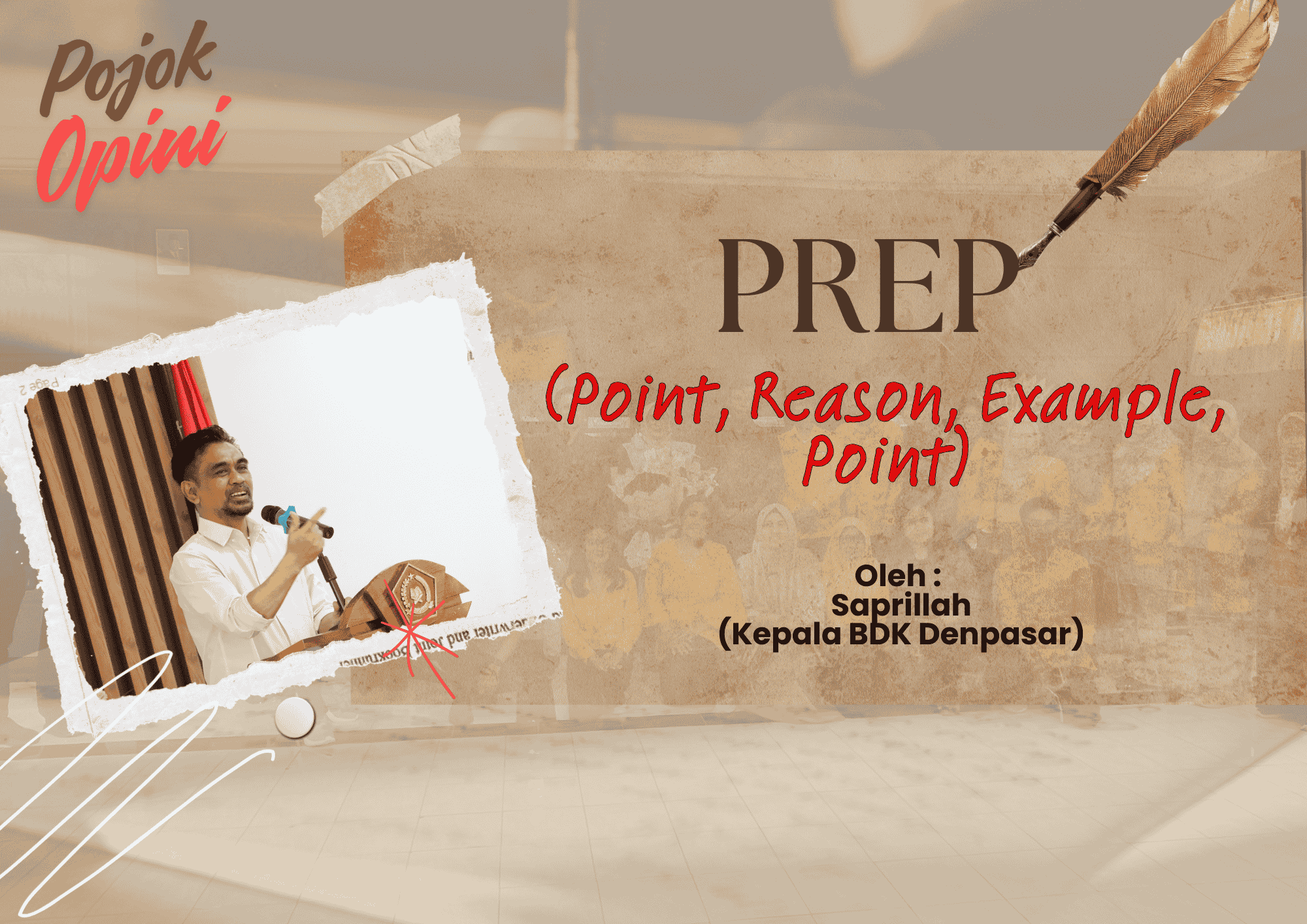

 5 Juni 2020
5 Juni 2020
 26 Desember 2022
26 Desember 2022