
Menanam Benih, Merawat Jiwa: Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta melalui Dialektika Sokratik dalam Pelatihan Guru
Pendahuluan
Situasi hiruk-pikuk transformasi pendidikan yang kian terakselerasi oleh digitalisasi, sering kali menjebak kita dalam labirin administratif yang kaku. Kurikulum sering kali dipandang sebagai deretan target capaian yang harus tuntas, sementara ruang kelas berubah menjadi pabrik pengolahan data, bukan taman persemaian jiwa. Sebagai Widyaiswara, kita berdiri di garda depan untuk bertanya: Di manakah letak "ruh" pendidikan jika interaksi antara guru dan murid hanya bersifat transaksional?
Penulis menawarkan sebuah antitesis terhadap “kekakuan” tersebut melalui implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Namun, cinta yang dimaksud di sini bukanlah sekadar afeksi sentimental, melainkan sebuah epistemologi dan tindakan pedagogis yang berani. Mengacu pada konsep Love Pedagogy yang diulas oleh Daaboul (2024), cinta dalam pendidikan adalah pondasi keamanan psikologis yang memungkinkan potensi intelektual siswa mekar tanpa rasa takut.
Socrates: Cinta dalam Bentuk Pertanyaan
Terinspirasi artikel Ninik Uswatun Fadhilah pada website BDK Denpasar, yang mengangkat metode Socrates dalam Kurikulum Berbasis Cinta, penulis mencoba membumikan konsep metode Sokrates dalam konteks pelatihan guru, salah satu bidang garap kami sebagai widyaiswara. Untuk mengaktivasi cinta ini di dalam ruang belajar, kita memerlukan instrumen yang kuat: Metode Socrates. Banyak yang keliru menganggap metode ini hanya alat untuk mempertajam kognisi. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Rusmana (2020), metode Socrates memiliki peran krusial dalam domain afektif.
Dengan bertanya secara dialektis, seorang guru sebenarnya sedang menunjukkan bentuk cinta tertinggi yakni rasa hormat terhadap kedaulatan berpikir siswa. Kita tidak lagi "menyuapi" jawaban, melainkan menjadi "bidan" yang membantu mereka melahirkan kebenaran dari dalam diri siswa sendiri. Dalam konteks pelatihan guru, metode ini mengubah kelas menjadi ruang kolaboratif di mana suara widyaiswara tidak lagi menjadi satu-satunya otoritas, melainkan pemantik bagi kesadaran kritis guru.
Metodologi Implementasi dalam Pelatihan
Sebagai Widyaiswara, tugas kita adalah menjembatani teori ini ke dalam praktik pelatihan yang konkret. Berikut adalah tiga langkah strategis yang dapat kita terapkan:
1. Modeling the Ethic of Care: Pelatihan harus dimulai dengan memvalidasi sisi kemanusiaan guru. Sebelum membahas substansi kurikulum, gunakan pertanyaan reflektif untuk menyentuh aspek afektif mereka. Sesuai pemikiran Nel Noddings (2013), hubungan "caring" antara pelatih dan peserta adalah prasyarat transfer ilmu yang efektif.
2. Socratic Workshop: Alihkan sesi ceramah menjadi sesi dialektika. Tantang guru untuk menyelesaikan masalah pedagogis di kelas melalui simulasi bertanya. Bukan menanyakan "Apa jawabannya?", melainkan "Mengapa kamu berpendapat demikian?" atau "Bagaimana perasaanmu jika berada di posisi siswa tersebut?".
3. Humanistic Redesign: Bimbing guru untuk mendesain modul ajar yang tidak hanya mengejar skor kognitif, tetapi juga memetakan pertumbuhan karakter. Riset Sunastri et al. (2025) menunjukkan bahwa kurikulum humanistik yang memprioritaskan cinta universal mampu meningkatkan motivasi intrinsik siswa secara signifikan.
Bagaimana "Kurikulum Berbasis Cinta" ini bekerja secara praktis? Berikut adalah skema implementasi
A. Fase Provokasi (Menanam Benih)
Jangan memulai sesi dengan slide materi. Mulailah dengan pertanyaan yang menggugat nilai moral mereka sebagai pendidik.
Contoh Pertanyaan: "Apakah tujuan akhir Anda mengajar adalah agar siswa lulus ujian, atau agar siswa mampu mencintai proses belajar?"
Aksi: Gunakan studi kasus dilematis yang tidak memiliki jawaban benar/salah secara hitam-putih.
B. Proses Dialektika (Merawat Jiwa)
Saat guru memberikan jawaban klise (misal: "Saya mengajar karena panggilan jiwa"), gunakan teknik Scaffolding Sokratik:
Pelacakan Konsistensi: "Jika itu panggilan jiwa, mengapa kita seringkali lebih fokus pada tumpukan administrasi daripada binar mata siswa yang kesulitan?"
Eksplorasi Konsekuensi: "Apa dampaknya bagi kesehatan mental siswa jika cinta kita pada kurikulum lebih besar daripada cinta kita pada individu?"
C. Refleksi Kolektif (Panen Makna)
Alih-alih memberikan kesimpulan, mintalah guru merumuskan "Manifesto Cinta" versi mereka sendiri berdasarkan dialog yang terjadi. Di sini, dialektika berfungsi menyatukan logika (instruksional) dengan hati (pedagogi kasih).
Jika kita sandingkan pola pelatihan yang selama ini kita lakukan dengan alternatif pelatihan Sokratik & Cinta tergambar pada tabel berikut:
Tabel Perbandingan: Tradisional vs. Sokratik Berbasis Cinta
|
Aspek |
Pelatihan Konvensional |
Pelatihan Sokratik & Cinta |
|
Peran Widyaiswara |
Narasumber / Pakar |
Fasilitator / Bidan Ide |
|
Metode |
Ceramah & Penugasan |
Dialog Mendalam & Refleksi |
|
Output |
Sertifikat & Keterampilan |
Transformasi Paradigma & Empati |
|
Fokus |
Kognitif (Tahu Apa) |
Eksistensial (Mengapa & Bagaimana Menjadi) |
Agar lebih operasional konkret, ilustrasi berikut sebagai visualisasi konsep implementasi metode Socrates berbasis Cinta. Salah satu tema yang sering menjadi "beban" bagi guru:
"Standar Kurikulum vs. Kebutuhan Emosional Siswa."
Skenario Dialog Sokratik: "Paradoks Sang Penabur"
Latar Belakang: Seorang peserta pelatihan (Guru) merasa tertekan karena harus mengejar target materi, sementara ia tahu beberapa siswanya sedang mengalami krisis motivasi atau masalah personal.
Widyaiswara (W): "Ibu, menurut Anda, apa tugas utama seorang petani saat menanam benih?"
Guru (G): "Tentu saja memastikan benih itu tumbuh dan menghasilkan buah, Pak."
W: "Jika tanahnya kering dan keras, apakah petani akan memarahi benih tersebut karena tidak tumbuh sesuai jadwal?"
G: "Tentu tidak. Petani akan menggemburkan tanah dan memberinya air."
W: "Menarik. Lalu dalam konteks kelas Ibu, manakah yang lebih penting: memastikan 'jadwal tanam' (kurikulum) selesai tepat waktu, atau memastikan 'tanah' (jiwa siswa) siap menerima benih tersebut?"
G: (Mulai ragu) "Idealnya keduanya, Pak. Tapi dinas menuntut kurikulum selesai di akhir semester."
W: "Jika Ibu berhasil menyelesaikan kurikulum tepat waktu, tetapi tanahnya tetap keras sehingga benih tidak pernah berakar, apakah Ibu merasa telah berhasil menjadi 'petani'?"
G: "Secara administratif mungkin iya, tapi secara batin... saya rasa saya gagal."
W: "Jika demikian, apakah 'Kurikulum Berbasis Cinta' itu berarti mengabaikan standar, atau justru berarti keberanian untuk berhenti sejenak demi menggemburkan tanah yang keras tadi?"
G: "Tapi bagaimana jika saya ditegur karena terlambat, Pak?"
W: "Manakah yang lebih menakutkan bagi jiwa seorang pendidik: ditegur oleh atasan karena keterlambatan administratif, atau 'ditegur' oleh masa depan siswa yang kehilangan gairah belajar karena kita terlalu terburu-buru?"
Penutup: Melampaui Kata, Menuju Makna
Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta melalui Dialektika Sokratik bukanlah sebuah teknik instruksional yang kaku, melainkan sebuah laku spiritual dalam ruang pelatihan. Widyaiswara tidak hadir untuk mengisi gelas yang kosong, melainkan untuk menyalakan api yang selama ini redup tertimbun tumpukan dogma dan beban administratif.
Melalui dialog-dialog Sokratik yang jujur dan tajam, kita tidak sedang meruntuhkan wibawa kurikulum, melainkan sedang memanusiakannya. Kita mengajak guru untuk kembali ke titik nol: melihat bahwa di balik setiap angka capaian pembelajaran, ada jiwa yang butuh dirawat, dan di balik setiap tujuan nasional, ada cinta yang harus menjadi kompas.
Pada akhirnya, menanam benih pengetahuan tanpa merawat jiwa sang penanam adalah sebuah kesia-siaan intelektual. Dengan meletakkan "Cinta" sebagai fondasi dan "Dialektika" sebagai jalan, kita sedang membangun sebuah ekosistem pendidikan di mana kebenaran tidak lagi dipaksakan dari atas, melainkan lahir dari rahim kesadaran kolektif. Sebab, hanya guru yang merasa dicintai dan dimanusiakan dalam ruang pelatihanlah yang akan mampu mencintai dan memanusiakan siswa-siswanya di ruang kelas
Pesan untuk Teman Sejawat
Di penghujung tulisan sedikit pesan buat rekan-rekan sejawat, mari kita ingat kembali bahwa tugas utama kita bukan sekadar memastikan guru paham regulasi, melainkan memastikan guru kembali mencintai profesinya. Pendidikan tanpa cinta adalah mekanisasi; pendidikan dengan cinta namun tanpa dialektika adalah indoktrinasi. Kita membutuhkan keduanya dalam keseimbangan yang harmonis.
Mari kita jadikan setiap sesi pelatihan sebagai oase dialektika, di mana cinta dan logika menari dalam irama yang sama. Karena pada akhirnya, kurikulum yang paling efektif bukanlah yang tertulis di atas kertas, melainkan yang terukir di dalam hati.
Referensi
Daaboul, Y. (2024). Love Pedagogy: Teachers Reflect On Love As An Educational Approach. Educational Administration: Theory and Practice.
Noddings, N. (2013). Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education. University of California Press.
Rusmana, N. (2020). The Implementation of Socratic Method in Affective Domain. International Journal of Innovation, Creativity and Change.
Sunastri, N. M., et al. (2025). Humanistic Curriculum Implementation: A Neo-Humanistic Perspective. International Journal of Social Sciences and Humanities.

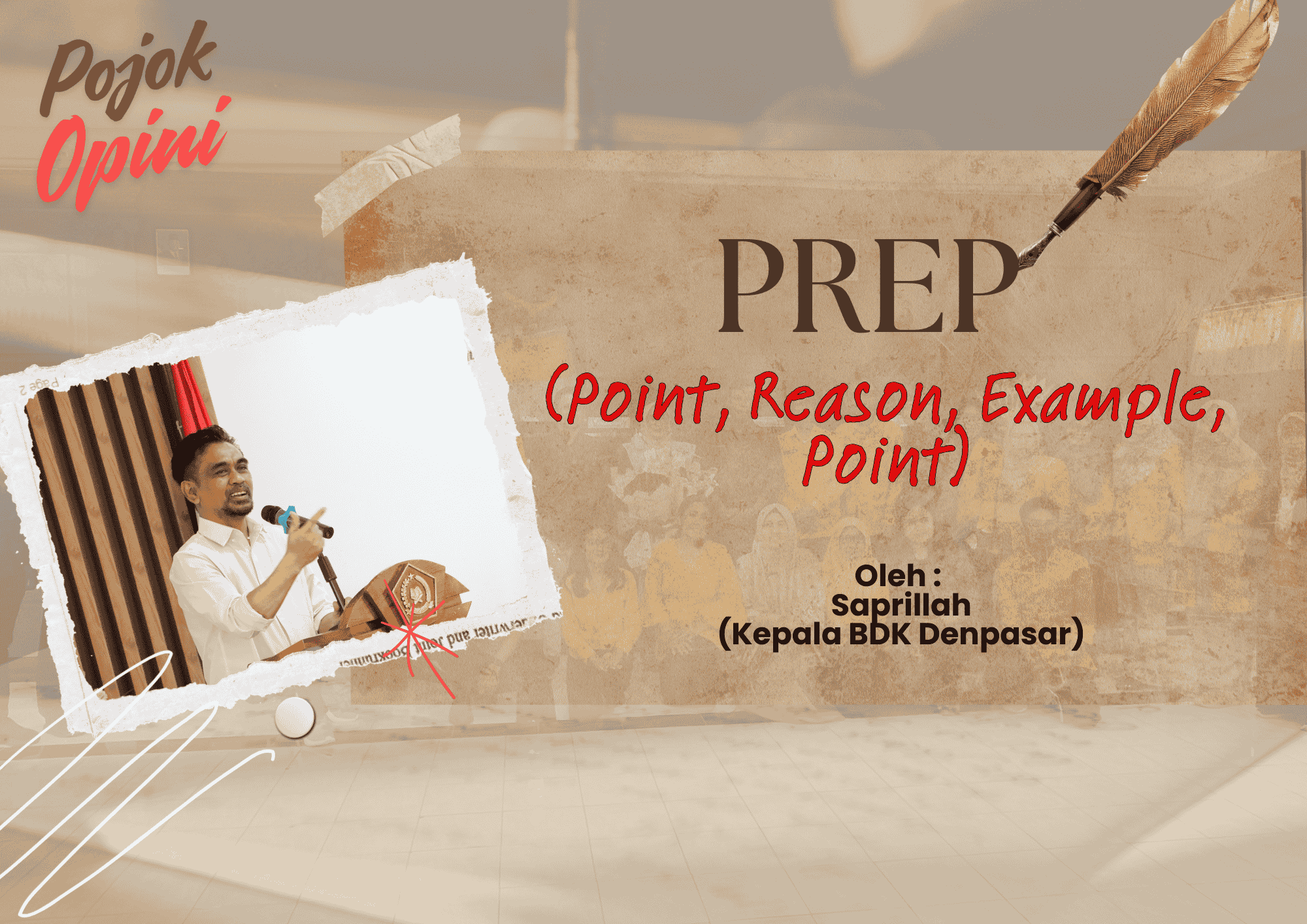


 5 Juni 2020
5 Juni 2020
 26 Desember 2022
26 Desember 2022