
Panggung, Disabilitas, dan Kurikulum Berbasis Cinta (Catatan Review and Design in Islamic Education Ditjen Pendis Kemenag RI)
Oleh : Saprillah (Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar)
Saya cenderung skeptis terhadap doa dan pembacaan kitab suci dalam acara seremonial. Bukan karena keduanya kehilangan legitimasi religius, melainkan karena terlalu sering diposisikan sebagai ritual pembuka yang netral, steril dari relasi kuasa, dan seolah berada di luar politik representasi. Padahal, justru di awal acara itulah etika sebuah panggung bekerja.
Acara ini dibuka dengan tilawah Al-Qur’an, lalu doa. Keduanya dibacakan oleh anak-anak madrasah tunanetra. Saya ingin menegaskan sejak awal: yang membuat peristiwa ini penting bukan karena mereka tunanetra, dan bukan pula karena hadirin “terharu”. Yang penting adalah cara panggung itu disusun.
Dalam banyak praktik, disabilitas kerap dihadirkan sebagai narasi moral: untuk membangkitkan empati, menegaskan kebajikan penyelenggara, atau sekadar menjadi bukti simbolik inklusivitas. Pola semacam ini justru problematik, karena menjadikan disabilitas sebagai objek afeksi, bukan sebagai subjek sosial.
Yang terjadi di sini berbeda.
Tilawah dan doa di awal acara itu tidak diletakkan sebagai momen emosional, tidak diberi bingkai narasi “keterbatasan”, dan tidak diposisikan sebagai kejutan dramatik. Anak-anak tunanetra tersebut tidak “dipamerkan”. Mereka dipercaya. Dan kepercayaan adalah kategori politik, bukan psikologis.
Di titik ini, panggung bekerja secara etis. Ia tidak menurunkan standar, tidak pula mengistimewakan secara simbolik. Ia menempatkan subjek disabilitas dalam posisi yang paling mendasar dalam sebuah seremoni keagamaan: pembuka ruang sakral. Ini bukan gestur belas kasih, melainkan praktik pengakuan.
Di sinilah saya melihat relevansi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). KBC tidak berbicara tentang cinta sebagai perasaan, melainkan sebagai kerangka relasional yang menolak hierarki martabat. Cinta, dalam pengertian ini, adalah keberanian institusional untuk memperlakukan subjek secara setara—tanpa romantisasi, tanpa reduksi.
Tilawah dan doa itu bekerja sebagai pedagogi publik. Ia mengajarkan sesuatu yang tidak pernah efektif diajarkan lewat modul: bahwa kesetaraan tidak perlu diumumkan, cukup dijalankan. Bahwa inklusi tidak selalu memerlukan bahasa moral, tetapi desain ruang yang adil.
Penting dicatat: keberhasilan momen ini justru terletak pada ketiadaan narasi berlebihan. Tidak ada penjelasan panjang tentang disabilitas. Tidak ada aplaus yang dipandu. Tidak ada jeda dramatis. Semua dibiarkan berlangsung sebagaimana mestinya. Inilah bentuk paling dewasa dari pengakuan: ketika perbedaan tidak perlu ditandai.
Dalam konteks institusi negara—khususnya Kementerian Agama—ini adalah praktik keberagamaan yang signifikan. Keberagamaan tidak hadir sebagai simbol dominasi normalitas, tetapi sebagai pengalaman bersama yang tidak menyingkirkan siapa pun dari pusat. Negara tidak sedang “memberi ruang”, melainkan berhenti memonopoli ruang.
Setelah rangkaian perayaan lintas iman, termasuk Natal bersama, pembuka acara ini bukan sekadar kelanjutan simbolik, tetapi penegasan arah. Dari toleransi yang retoris menuju keadilan yang operasional. Dari empati yang ditonton menuju pengakuan yang dijalankan.
Jika Kurikulum Berbasis Cinta ingin dipahami secara serius, maka peristiwa semacam ini adalah contohnya. Bukan karena ia mengharukan, tetapi karena ia tepat secara etis. Panggung tidak digunakan untuk memproduksi rasa, melainkan untuk mendistribusikan martabat.
Dan di situlah cinta bekerja—bukan sebagai kata, tetapi sebagai struktur.


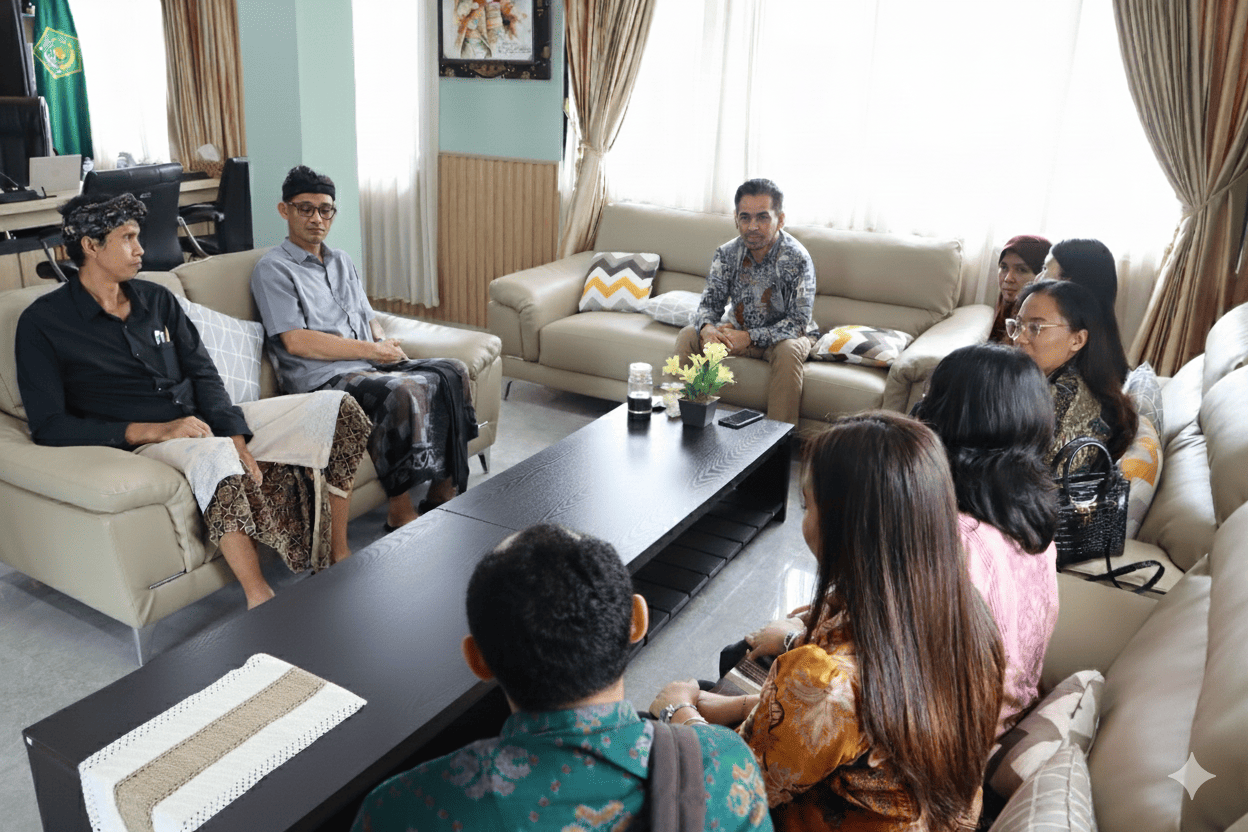
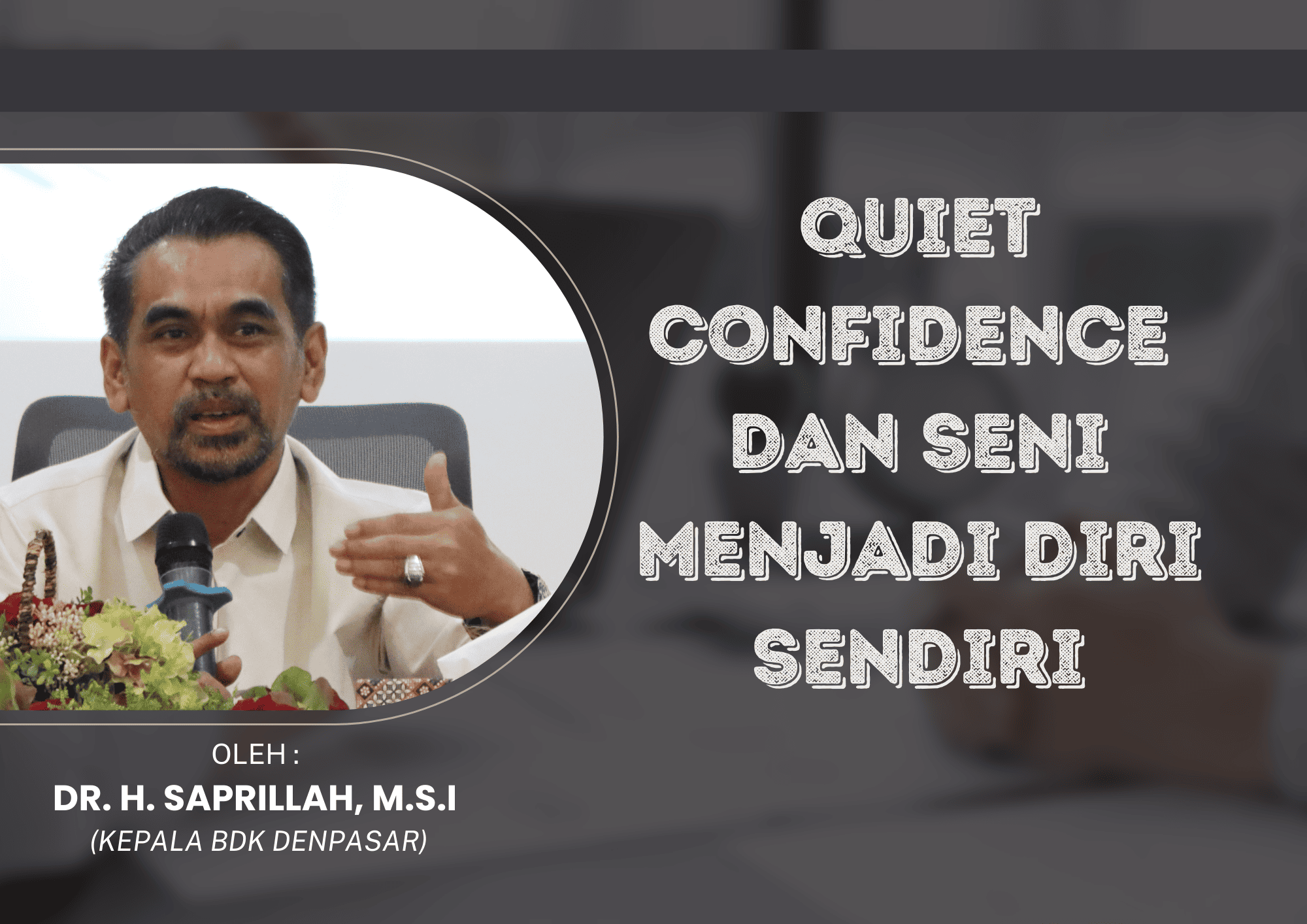
 5 Juni 2020
5 Juni 2020
 26 Desember 2022
26 Desember 2022